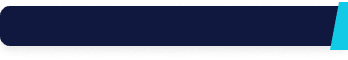Sate Kere, dari Lidah Rakyat Jelata Kini Digandrungi Orang Kaya

Sate Kere, dari Lidah Rakyat Jelata Kini Digandrungi Orang Kaya
A
A
A
Siang belum lama beranjak, tetapi lapak Mbak Tug di pinggir Jalan Arifin, Kepatihan Kulon, Jebres, Kota Solo sudah terlihat sesak. Pengunjung hilir mudik berdatangan demi mencicipi kuliner khas Solo, sate kere. Uniknya, kendati istilah kere jelas bermakna miskin, pembeli sate di lapak ini sama sekali tak menunjukkan orang tak berpunya.
Tak tampak orang miskin di lapak ini. Para pembeli yang terlihat pada pertengahan Desember 2019 lalu justru banyak mengendarai mobil pribadi. Dilihat dari pelat mobilnya, sebagian juga berasal dari luar Kota Solo. Begitu ramainya, untuk jajan di lapak sederhana Mak Tug terkadang harus rela antre.
“Tiap hari dagangan selalu habis. Ya, kalau dirata-rata omzet Rp2,5 juta per hari,” ujar Marimin, 60, sang penjual. Omzet jutaan rupiah tidak didapatkan Marimin hingga berjam-jam. Dia mulai membuka lapak pukul 13.00 WIB. Tiga jam berikutnya atau sekitar pukul 16.00 WIB, dia biasanya sudah menutup seluruh dagangan lantaran habis terjual.
Sate kere perlahan menjadi ikon kuliner khas Kota Solo. Bagi para pendatang, berkunjung ke kota asal Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini tak lengkap jika belum mencicipi sate ini. Sesuai namanya, sate ini sangatlah sederhana. Tak seperti sate kebanyakan yang berisi daging, sate kere berisi gembus, tempe kedelai, dan jeroan sapi.
Dilihat bahannya, sate ini wajar diidentikkan sebagai milik orang kere. Harganya pun sangat murah. Untuk satu tusuk sate gembus dan lontong harganya hanya Rp3.000. Namun kelezatan sate kere tak lagi milik rakyat jelata. Kini sate ini telah berubah dan naik kelas menjadi makanan kelas atas.
Pamor sate kere kian meroket mulai 2001. Di balik merebaknya warisan kuliner khas Solo ini juga ada cerita menarik di belakangnya. Sate kere lahir memang sebagai konsumsi orang-orang miskin Solo kala masa kolonial. Tak sekadar makanan, sate ini hakikatnya juga bentuk perlawanan rakyat Solo terhadap kuliner kolonial saat itu.
Peneliti sejarah kuliner Solo Heri Priyatmoko mengatakan, dalam atlas kuliner Nusantara, kuliner sate kere memiliki riwayat yang pekat dengan nasib getir dan perjuangan rakyat kelas bawah. Bahan-bahan sate kere seperti gembus, tempe kedelai, dan jeroan sapi di masa kolonial dijauhi pembesar Eropa dan bangsawan. Bahkan gembus dan jeroan merupakan pantangan untuk disajikan di meja makan.
Pada 1849 ada kebijakan tentang pemotongan sapi dan kerbau. Jeroan dan gajih yang disingkirkan selanjutnya dimanfaatkan masyarakat bawah yang tak sanggup membeli daging atau membeli sate. Bahan buangan itu kemudian diolah bersama gembus yang selanjutnya dikenal dengan sate kere.
Sate kere Solo kini juga sudah go international. Lapak Mbak Tug misalnya kerap kali menerima pesanan orang-orang Indonesia yang tengah kuliah atau bekerja di luar negeri. Yang dipesan sambalnya untuk oleh-oleh di sana. Ada yang dari Inggris, Hong Kong, dan Australia,” beber Marimin.
Orang tua Marimin dulu mulai berjualan pada 1977. Saat itu dagangan masih disunggi (diletakkan di atas kepala) dan dijual berkeliling. Seiring makin terkenalnya sate kere, Marimin juga mengaku beberapa kali diundang pemerintah kota untuk mengikuti pameran di luar daerah.
Kini lapaknya diberi nama Sate Presiden. Perubahan nama ini dilatarbelakangi lantaran lapaknya jadi langganan Presiden Jokowi, termasuk saat mendapat pesanan untuk sajian tamu Jokowi kala mantu anak perempuannya, Kahiyang Ayu.
Sisa Daging Diolah Jadi Tengkleng
Selain sate kere, ada kuliner tengkleng yang juga bentuk perlawanan moral kala itu. Tengkleng diperkirakan muncul sekitar satu abad lalu dari aksi para buruh yang memunguti sisa-sisa daging kambing juragan batik Solo. Sekelompok buruh yang tidak mampu menjangkau makanan berkelas lantas mengolah tulang dan jeroan kambing untuk disantap.
Namun, menurut Heri Priyatmoko, argumentasi itu dinilai terlalu dangkal dan analisis minim data. “Yang pasti tengkleng lahir dari kreativitas orang Solo dalam menghadapi situasi yang mencekik, tepatnya di masa penjajahan Jepang,” katanya.
Di Solo, kuliner tengkleng antara lain bisa ditemui di Warung Yu Tentrem di Jalan Letjend Sutoyo, Gang Kelud Selatan, Ngadisono RT 4 RW 14, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari. Tengkleng Yu Tentrem sudah lama dikenal karena rasanya lezat, mantap, enak, serta khas dari Solo. Resep masakan turun-temurun tetap dipertahankan kualitasnya sampai sekarang. Bahkan tengkleng Yu Tentrem telah menjadi langganan keluarga mantan Presiden Soeharto hingga Jokowi.
Medio 1980 silam, Tentrem mulai berjualan tengkleng berkeliling Kota Solo dengan berjalan kaki. Satu panci tengkleng dan kuah digendong dari rumah ke rumah menyambangi pembeli. Untuk wadah makanannya kala itu masih menggunakan daun pisang yang dalam bahasa Jawa disebut pincuk. Untuk dapat menikmati tengkleng Yu Tentrem harus antre karena peminatnya banyak.
Warung yang dibuka mulai pukul 10.00 WIB ini biasanya sudah habis jualannya sekitar pukul 13.00 WIB. Pandangan tengkleng sebagai makanan rakyat jelata pun kini sudah tidak ada. Bahkan penikmatnya merupakan orang-orang kaya dari berbagai latar belakang dan suku.
Tengkleng mulai berkibar sekitar tahun 2013. “Saat itu banyak festival kuliner yang diselenggarakan dan tengkleng yang diangkat,” kata Winarno, salah satu anak Yu Tentrem.Selain sate kere dan tengkleng, ada kuliner lain Solo yang khas, yakni selat.
Warung Selat Mbak Lies di Serengan Nomor 42 RT 03 RW 02, Solo, adalah salah satu yang masyhur. Rahasia selat Mbak Lies tetap lezat sampai sekarang adalah cara memasaknya. “Aktivitas memasak sampai sekarang tetap pakai anglo untuk yang besar-besar karena berpengaruh pada rasa,” ungkap Wulandari Kusmadyaningrum selaku pemilik usaha.
Dirinya belajar autodidak membuat selat dan mulai membuka warung 1987 lalu. Namun meski tenar, menurut Heri Priyatmoko, cerita panjang selat sebagai mahakarya dapur Solo belum terkuak. “Yang kita dapat juga menyesatkan. Keliru kalau mengatakan selat diadaptasi dari salad atau slatjee dalam bahasa Belanda. Kata slatjee sudah tidak tepat untuk salad yang betul ialah slaatje, “ kata Heri.
Dengan petunjuk kamus bahasa Belanda, terlacak bahwa slachtje kurang lebih artinya hasil pemotongan daging yang dijadikan kecil-kecil. Kala itu lidah orang Jawa sulit melafalkan slachtje meniru lidah orang Eropa. Selain slachtje bahan selat adalah aardappel (kentang), wortelen (wortel), boon (buncis), komkommer (ketimun), sla (slada), ei (telur), dan sojasous (kuah kecap), serta saus mayones. (ARY WAHYU WIBOWO)
Tak tampak orang miskin di lapak ini. Para pembeli yang terlihat pada pertengahan Desember 2019 lalu justru banyak mengendarai mobil pribadi. Dilihat dari pelat mobilnya, sebagian juga berasal dari luar Kota Solo. Begitu ramainya, untuk jajan di lapak sederhana Mak Tug terkadang harus rela antre.
“Tiap hari dagangan selalu habis. Ya, kalau dirata-rata omzet Rp2,5 juta per hari,” ujar Marimin, 60, sang penjual. Omzet jutaan rupiah tidak didapatkan Marimin hingga berjam-jam. Dia mulai membuka lapak pukul 13.00 WIB. Tiga jam berikutnya atau sekitar pukul 16.00 WIB, dia biasanya sudah menutup seluruh dagangan lantaran habis terjual.
Sate kere perlahan menjadi ikon kuliner khas Kota Solo. Bagi para pendatang, berkunjung ke kota asal Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini tak lengkap jika belum mencicipi sate ini. Sesuai namanya, sate ini sangatlah sederhana. Tak seperti sate kebanyakan yang berisi daging, sate kere berisi gembus, tempe kedelai, dan jeroan sapi.
Dilihat bahannya, sate ini wajar diidentikkan sebagai milik orang kere. Harganya pun sangat murah. Untuk satu tusuk sate gembus dan lontong harganya hanya Rp3.000. Namun kelezatan sate kere tak lagi milik rakyat jelata. Kini sate ini telah berubah dan naik kelas menjadi makanan kelas atas.
Pamor sate kere kian meroket mulai 2001. Di balik merebaknya warisan kuliner khas Solo ini juga ada cerita menarik di belakangnya. Sate kere lahir memang sebagai konsumsi orang-orang miskin Solo kala masa kolonial. Tak sekadar makanan, sate ini hakikatnya juga bentuk perlawanan rakyat Solo terhadap kuliner kolonial saat itu.
Peneliti sejarah kuliner Solo Heri Priyatmoko mengatakan, dalam atlas kuliner Nusantara, kuliner sate kere memiliki riwayat yang pekat dengan nasib getir dan perjuangan rakyat kelas bawah. Bahan-bahan sate kere seperti gembus, tempe kedelai, dan jeroan sapi di masa kolonial dijauhi pembesar Eropa dan bangsawan. Bahkan gembus dan jeroan merupakan pantangan untuk disajikan di meja makan.
Pada 1849 ada kebijakan tentang pemotongan sapi dan kerbau. Jeroan dan gajih yang disingkirkan selanjutnya dimanfaatkan masyarakat bawah yang tak sanggup membeli daging atau membeli sate. Bahan buangan itu kemudian diolah bersama gembus yang selanjutnya dikenal dengan sate kere.
Sate kere Solo kini juga sudah go international. Lapak Mbak Tug misalnya kerap kali menerima pesanan orang-orang Indonesia yang tengah kuliah atau bekerja di luar negeri. Yang dipesan sambalnya untuk oleh-oleh di sana. Ada yang dari Inggris, Hong Kong, dan Australia,” beber Marimin.
Orang tua Marimin dulu mulai berjualan pada 1977. Saat itu dagangan masih disunggi (diletakkan di atas kepala) dan dijual berkeliling. Seiring makin terkenalnya sate kere, Marimin juga mengaku beberapa kali diundang pemerintah kota untuk mengikuti pameran di luar daerah.
Kini lapaknya diberi nama Sate Presiden. Perubahan nama ini dilatarbelakangi lantaran lapaknya jadi langganan Presiden Jokowi, termasuk saat mendapat pesanan untuk sajian tamu Jokowi kala mantu anak perempuannya, Kahiyang Ayu.
Sisa Daging Diolah Jadi Tengkleng
Selain sate kere, ada kuliner tengkleng yang juga bentuk perlawanan moral kala itu. Tengkleng diperkirakan muncul sekitar satu abad lalu dari aksi para buruh yang memunguti sisa-sisa daging kambing juragan batik Solo. Sekelompok buruh yang tidak mampu menjangkau makanan berkelas lantas mengolah tulang dan jeroan kambing untuk disantap.
Namun, menurut Heri Priyatmoko, argumentasi itu dinilai terlalu dangkal dan analisis minim data. “Yang pasti tengkleng lahir dari kreativitas orang Solo dalam menghadapi situasi yang mencekik, tepatnya di masa penjajahan Jepang,” katanya.
Di Solo, kuliner tengkleng antara lain bisa ditemui di Warung Yu Tentrem di Jalan Letjend Sutoyo, Gang Kelud Selatan, Ngadisono RT 4 RW 14, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari. Tengkleng Yu Tentrem sudah lama dikenal karena rasanya lezat, mantap, enak, serta khas dari Solo. Resep masakan turun-temurun tetap dipertahankan kualitasnya sampai sekarang. Bahkan tengkleng Yu Tentrem telah menjadi langganan keluarga mantan Presiden Soeharto hingga Jokowi.
Medio 1980 silam, Tentrem mulai berjualan tengkleng berkeliling Kota Solo dengan berjalan kaki. Satu panci tengkleng dan kuah digendong dari rumah ke rumah menyambangi pembeli. Untuk wadah makanannya kala itu masih menggunakan daun pisang yang dalam bahasa Jawa disebut pincuk. Untuk dapat menikmati tengkleng Yu Tentrem harus antre karena peminatnya banyak.
Warung yang dibuka mulai pukul 10.00 WIB ini biasanya sudah habis jualannya sekitar pukul 13.00 WIB. Pandangan tengkleng sebagai makanan rakyat jelata pun kini sudah tidak ada. Bahkan penikmatnya merupakan orang-orang kaya dari berbagai latar belakang dan suku.
Tengkleng mulai berkibar sekitar tahun 2013. “Saat itu banyak festival kuliner yang diselenggarakan dan tengkleng yang diangkat,” kata Winarno, salah satu anak Yu Tentrem.Selain sate kere dan tengkleng, ada kuliner lain Solo yang khas, yakni selat.
Warung Selat Mbak Lies di Serengan Nomor 42 RT 03 RW 02, Solo, adalah salah satu yang masyhur. Rahasia selat Mbak Lies tetap lezat sampai sekarang adalah cara memasaknya. “Aktivitas memasak sampai sekarang tetap pakai anglo untuk yang besar-besar karena berpengaruh pada rasa,” ungkap Wulandari Kusmadyaningrum selaku pemilik usaha.
Dirinya belajar autodidak membuat selat dan mulai membuka warung 1987 lalu. Namun meski tenar, menurut Heri Priyatmoko, cerita panjang selat sebagai mahakarya dapur Solo belum terkuak. “Yang kita dapat juga menyesatkan. Keliru kalau mengatakan selat diadaptasi dari salad atau slatjee dalam bahasa Belanda. Kata slatjee sudah tidak tepat untuk salad yang betul ialah slaatje, “ kata Heri.
Dengan petunjuk kamus bahasa Belanda, terlacak bahwa slachtje kurang lebih artinya hasil pemotongan daging yang dijadikan kecil-kecil. Kala itu lidah orang Jawa sulit melafalkan slachtje meniru lidah orang Eropa. Selain slachtje bahan selat adalah aardappel (kentang), wortelen (wortel), boon (buncis), komkommer (ketimun), sla (slada), ei (telur), dan sojasous (kuah kecap), serta saus mayones. (ARY WAHYU WIBOWO)
(don)